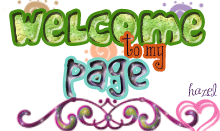| Berita Peristiwa - Berita Peristiwa |
| Sabtu, 15 Agustus 2009 00:05 |
 Pura di Bali/Ilustrasi Denpasar, beritabaru.com - Guru besar Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar Prof I Wayan Dibia menilai, kesenian dalam kehidupan masyarakat Bali mengalami pergeseran ke arah material. Akibatnya, kesenian di 'Pulau Seribu Pura' itu, kehilangan karisma. |
Kesenian Masyarakat Bali, Kehilangan Karisma Berita Peristiwa - Berita Peristiwa
Jumat, 13 November 2009
Seni Bali Kehilangan Taksu
Kesenian dalam kehidupan masyarakat Bali, kini mengalami pergeseran ke arah material (materialisme), yang mengakibatkan kesenian Bali kehilangan taksu (karisma). Demikian Guru Besar Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar Prof.Dr. I Wayan Dibia.
Menurut Dibia, taksu sangat diperlukan dalam semua bidang profesi dan masyarakat Bali meyakini, taksu sangat menentukan keberhasilan garapan karya seni. Masyarakat Bali, juga memandang taksu sebagai kekuatan yang dapat memberi kecerdasan dan kewibawaan kepada pemiliknya. Sekaligus sebagai jiwa, daya pikat bagi karya seni yang dihasilkan.
“Pegelaran atau ciptaan karya seni yang memiliki taksu, akan menjadi hidup dan berjiwa, sehingga dapat menggetarkan perasaan para penikmatnya,” ujar Prof Dibia.
Kreativitas seni tanpa taksu akan menjadi hampa dan hambar, sehingga tidak mampu membangkitkan cita-rasa bagi penikmat seni. Memang, taksu selama ini lebih banyak dikaitkan dengan seni, meskipun dalam realitasnya sangat dibutuhkan dalam semua bidang profesi.
Dalam tradisi Bali, pencapaian taksu seringkali melalui atau proses kegiatan ritual. “Di Bali dan tempat lain di Indonesia maupun belahan dunia, masyarakatnya percaya, bahwa seni adalah ciptaan Tuhan, dan mereka yakin kualitas suatu pegelaran ditentukan oleh datangnya sinar suci Tuhan (yang juga dikenal sebagai taksu),” ucap Prof Dibia.(*o/ant)
Jumat, 06 November 2009
Pendapat tentang Taksu

Berbagai pendapat tentang Taksu dari bebersps sumber:
BUDAYA TAKSU = BUDAYA PALSU (Membongkar Peta Pemikiran Seni dan Budaya Bali)
I Ngurah Suryawan *)
“…Pleidoi bagi kegagalan lahirnya maestro Perupa…Kerinduan lahirnya karya perupa Bali yang memberikan spirit pada peradabannya, semakin saja menggumpal. Kerinduan itu setara dengan dambaan atas lahirmya karya seni bertaksu…”1
Sebuah gerakan seni rupa, ketika hadir pada publik dan menawarkan visinya ia sebenarnya telah memberikan semua tawaran, tumpahan kemuakan serta ide perubahannya akan kondisi mapan yang dilihatnya. Cuma, memang tidak sesederhana hanya menyatakan kemuakan dan mengajukan tawaran perubahan, satu yang pasti bagi gerakan perubahan sosial –termasuk gerakan pembaharuan seni rupa– ia harus menjadi pioner untuk memperjuangan ide perubahannya itu sambil menyebarkan idenya pada komunitas dan masyarakat. Hingga suatu saat perubahan yang diinginkan, dicita-citakan –tentunya tanpa keadilan– akan menguji proses, kualitas gerakan kesenian itu; untuk memelihara ide perubahan dalam kesenian dan membentuk peta pemikiran baru tentang kesenian, kebudayaan.
Sungguh idealis memang, tapi mengusung idealisme adalah sebuah pilihan. Kehebatanmu tidak ditunjukkan dengan kemapuanmu, tapi pada pilihanmu1 . Sebuah pilihan adalah sebuah keyakinan dan hanya orang yang bisa memilih jalan hidup dan jalan keseniannyalah orang yang berprinsip dan yakin akan jalan hidupnya.
Setidaknya itulah yang diusung Komunitas Klinik Seni TAXU dengan segala konsekuensi atas pilihannya itu. Salah satunya memperjuangkan sendiri pilihan, keyakinan dan prinsip berkeseniannya. Kini, komunitas bebas yang banyak terdiri dari alumni dan mahasiswa STSI Denpasar kembali hadir dalam “Hati-Hati! Ada Upacara TAXU!!!”2 dari tanggal 25 Januari–8 Februari 2003. Setiap minggunya akan diisi dengan diskusi Kritik Kebudayaan Bali: Sebuah Pertanggungjawaban, serta pemutaran film Frida dan diskusi Frida Kahlo sebagai ikon Hollywood. Tempatnya pun hanya sebilik rumah disebuah perumahan sangat sederhana yang dijadikan art space, juga markas komunitas ini.
Apa yang akan mereka hadirkan? Dan rasanya sangat tidak bertanggungjawab dan terkesan emosional jika kita langsung menuduh mereka kelompok anak muda frustrasi3 yang tidak digoreng, tidak dapat kesempatan pameran di galeri ”top” di Bali. Siapa tahu apa yang mereka hadirkan bisa menyegarkan, mengurai dan membongkar ulang peta pemikiran kesenian dan kebudayaan di Bali (Indonesia).
TAXU: SEKILAS LINTAS
Kehadiran TAXU sebenarnya berawal dari kegelisahan. Rasanya tidak berlebihan jika menyebut sejarah Mendobrak Hegemoni Kamasra STSI Denpasar sebagai awal dan kelompok-kelompok perupa muda di kampus ini yang belum mendapat ruang seide dengan mereka. Kedua kelompok ini bertemu dan merefleksikan kegiatan mereka selama berkesenian. Dengan kumpul-kumpul dan diskusi di kampus, di sebuah rumah kos seorang kawan, atau kumpul di kos bersama.
Di kampus STSI Denpasar sebenarnya banyak kelompok perupa yang berjalan tanpa gairah dengan rutinitas pameran yang membosankan. Obrolan hanya berkisar pada promosi akan pameran, berapa laku atau di bawa makelar (expatriate) ke luar negeri. Ya, tentu saja kebanggaan telah menjadi pelukis terkenal untuk ukuran STSI atau Bali. Tapi semua tersentak, tensi kesenian menjadi memanas ketika di bulan Februari 2001 hadir gerakan MendobrakHegemoni. Awal yang biasa saja sebenarnya dengan pamflet dua halaman “Isu Paling Gress!!!”.4 Seolah mengacak-ngacak semua peta pemikiran kesenian yang ada, kehadiran yang mengundang kontroversi, ketersinggungan.
Tapi dibalik kritik yang terlihat vulgar, terlalu personal, ada suatu maksud –tentunya visi dan konsep kesenian– untuk memeriksa kembali pemain seni rupa dan bekerjanya secara adil dan jujur infrastruktur seni rupa. Inilah yang dikritik dalam karya-karya Mendobrak.5
Ternyata arus balik berbeda dan lebih sangar. Yang dikritik, termasuk SDI (Sanggar Dewata Indonesia), Nyoman Erawan, Gunarsa, Wianta, kritikus, media massa balik menyerang dan memusuhi kelompok dan gerakan ini. Sialnya, lembaga STSI Denpasar tempat mahasiswa ini bernaung ikut juga menghimpit mereka dengan pemanggilan mahasiswa, dialog sepihak dengan SDI dan yang paling menyesakkan tentunya permintaan maaf secara langsung dan lewat media massa pada SDI dan pihak yang tersinggung dengan Mendobrak6 . Semua dilakukan oleh lembaga tanpa sama sekali melibatkan Kamasra yang terlibat dalam Mendobrak.
Pasca Mendobrak, bukan hanya lembaga yang menekan, lingkungan mahasiswa di STSI juga “memusuhi” anak muda yang dituduh frustrasi ini. Lambat laun ternyata kelompok ini menyebar benihnya. Pertama di kampus tercatat sapihan mereka kembali beraksi dengan pamflet-pamflet dari Maret–Mei 2001. Tercatat pamflet seni aksi, buletin SUAKA (Solidaritas Untuk Aksi KAmasra), Membongkar Sejarah Seni Rupa Bali, Seni Kritik dan Penyadaran, Kiri SampaiMati, Sikat Gigi Erawan Harus Disikat. Pamflet ini selain disebar dan ditempel di kampus juga disebar saat aksi di ruang publik. Terutama saat Sikat Gigi Erawan dipentaskan di Puputan Badung7 .
Saat yang paling menegangkan tentunya saat pameran Pesta Kapitalisme Bali Juni 2001 sebagai kritik dari PKB (Pesta Kesenian Bali) yang membosankan itu. Sebelum pameran, terjadi pemanggilan mahasiswa, teror, perusakan karya-karya oleh lembaga STSI Denpasar melalui Satpam, pengusiran mahasiswa sampai adanya jam malam 20.00 WITA di kampus. Rangkaian teror terbukti dengan main ancamnya staf dosen STSI Denpasar yang mengadukan mahasiswa pada polisi.
Akhirnya, 16 Juni 2001 dibuka pameran kontra PKB di halaman depan museumLatta Mahosadhi disertai penyebaran pamflet “Pemerintah Kolonial Bali”8 . Saat inilah terjadi pembongkaran paksa pameran oleh lembaga STSI Denpasar yang langsung dipimpin Ketuanya, Prof. I Wayan Dibia beserta Pembantu Ketua. STSI menganggap pameran kontra PKB sebagai bentuk pembangkangan mahasiswa terhadap lembaga STSI, juga pameran ini tidak sesuai dengan ijin dan prosedur. Pameran kontra PKB ini dilanjutkan di depan kampus Universitas Udayana Sudirman, depan kampus Fakultas Sastra di Jalan Pulau Nias dan berakhir 24 Juni 20019 .
Berikutnya mulailah tradisi diskusi dan refleksi aksi kesenian dalam lingkungan komunitas seni pasca Mendobrak. Sedikit demi sedikit jumlah mahasiswa yang terkumpul tambah banyak dan diwadahi dalam diskusi seni rupa setiap Senin dan Kamis di sebuah rumah kos seorang kawan. Dari diskusi dan kumpul beberapa kali terwujudlah ide untuk melembagakan gerakan kesenian baru ini dalam sebuah komunitas seni, sebuah Klinik Seni pada September 2001. Namanya pun disepakti TAXU, plesetan/parodi dari kata-kata Taksu yang jamak digunakan di Bali untuk menjelaskan keangkeran, kemistisan kesenian dan upacara agama di Bali. Kelahirannyapun bertitik tolak untuk melakukan kritik dan deskaralisasi dan menghancurkan mitos-mitos kesenian dan kebudayaan Bali (Indonesia).
Tidak hanya melakukan diskusi, terbitlah pertama kali buletin seni rupa KITSCH10 yang mewadahi pemikiran alternatif tentang seni rupa dari anggota TAXU dan juga peminat seni rupa lainnya. Untuk pertama kali edisinya mengangkat “Kebohongan Pengider Bhuana” sebagaikritik pameran bersama Pengider Bhuana dosen STSI Denpasar di Museum Rudana, Agustus 2002.
Kini mereka hadir kembali lewat Hati-Hati!… sebagai pameran perdana komunitas TAXU. Layak disimak apakah hasil diskusi, refleksi dan prinsip kesenian mereka akan teruji. Juga bagaimana mereka bisa “bermain” dan menempatkan diri dalam pertarungan seni rupa Bali dan juga Indonesia. Juga kepada beberapa infrastruktur kesenian yang dulu mereka kritik lewat Mendobrak. Kini apa tawaran mereka bagi pembongkaran pemikiran kesenian dan kebudayaan Bali (Indonesia)?
HATI-HATI!… SEBUAH TAWARAN WACANA
Satu yang pasti dari kehadiran TAXU dan Hati-Hati!… tentunya adalah tawaran wacana alternatif pemikiran kesenian dan kebudayaan Bali. Ini didasari dengan penguatan kembali terhadap kritik kekuasaan kesenian, keterbukaan dan kejujuran pasar –yang tentu saja relatif–dalam dunia seni rupa Bali (Indonesia). Bingkai awalnya telah hadir dalam Mendobrak dan kini dilanjutkan lebih dalam dalam kritik kebudayaan Bali. Analisis terhadap kelicikan pasar dan kongsi mafia seni rupalah –sebagai bagian dari perangkat seni rupa– yang memicu untuk kembali membongkarnya dalam bingkai kritik kebudayaan Bali dan Indonesia secara umum.
Dalam 20-an karya seni lukis, instalasi, kriya dari belasan perupa hadir sebagai bentuk pernyataan-pernyataan sikap mereka dalam berkesenian dan merespons fenomena kebudayaan kontemporer Bali dan Indonesia masakini. Ada juga yang menghadirkan karya seni konseptual (conceptual art) dalam beberapa karya. Tapi yang terbanyak memang karya lukis ataupun instalasi menyikapi fenonema kekerasan Pecalang (Polisi Adat), paradoks manusia Bali, fasisme dan sentimen terhadap pendatang. Ada juga karya repetisi sablon Pecalang dan figur Dr. Wayan Rai S, Ketua STSI Denpasar. Sebagai pernyataan atas bagaimana lembaga pendidikan tinggi seni satu-satunya di Bali –lewat simbol Ketuanya– telah memberikan sumbangan sangat berharga dalam memasung kreativitas, daya kritis mahasiswa dan menjadi bagian besar dalam infrastruktur seni yang harus dikritik.
Dalam konsep karya seni, pernyataan seniman yang dituangkan lewat karya visual lukis atau instalasi dinding adalah salah satu modal dan tawaran pada publik untuk diapresiasi. Di samping tentunya penggarapan sempurna yang terkait dengan teknik. Agaknya kekuatan dalam pernyataan pada karyalah yang menjadi kekuatan utama pameran ini, di samping teknis penggarapan yang mendekati sempurna dari senimannya.
Beberapa karya yang dipamerkan merepresentasikan semua itu. Lihat misalnya Muliana Bayak dalam Powerfull Jacket, 2003, mixed media (instalasi dingding). Memajang dua buah rompi loreng yang sering dipakai pecalang di Bali. Cukup sederhana, tinggal disablon Pecalang Banjar A misalnya. Kini dengan berkaian adat Bali, memakai destar dan menggunakan rompi bertuliskan pecalang seakan sudah bisa “berkuasa” di jalan-jalan ketika ada upacara agama. Belum lagi bisa masuk dan menonton gratiskonser Sheila On 7 hanya dengan menggunakan rompi ini. Warna loreng-loreng yang dipilih merepersentasikan bagaimana pecalang saat ini mirip dengan tentara sipil (militia). Juga dalam hubungannya dengan negara dan kekuasaan. Pecalang sangat sering diberikan penyuluhan dan bimbingan ketertiban dan keamanan oleh Bimas (Bimbingan Masyarakat) Polisi Daerah Bali. Sederhananya Pecalang “dipelihara” oleh polisi dan juga tentara. Ini dikuatkan dengan adanya Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur wewenang dan tugas pecalang dalam Desa Pekraman di Bali.
Pernyataan yang sama, kritik terhadap militerisasi sipil pecalang ini hadir lewat karya Kacrut, Pecalang, 2003, 120×240 cm, mixed media. Kali ini lebih menampakkan perulang an(repetisi) gambar Pecalang dengan sablon hitamputih. Bentuk pecalangpun terlihat jelas dalam repetisi dengan gambar kain, memakai rompi dengan lambang desa adat tertentu di Bali dan dibawahnya tertulis Pecalang. Repetisi gambar pecalang yang sangar, dengan kumis dan jenggot juga terlihat dengan jelas. Karya lainnya adalah Mulyana bayak, Pecalang Uniform, 2003, 100×140 cm, oil on canvas. Pecalang kni sudah menjadi trendy dan jaminan rasa aman bagi masyarakat. Layaknya sebuah tren fashion dalam busana, pakaian pecalang dengan poleng (hitam-putih) juga mengesankan trendy, kewibawaan dan juga eksotis. Fenomena ini sungguh paradoks dengan bagaimana pecalang menjadi latah dimanfaatkan untuk perayaan kegiatan modern dengan bertameng adat. Pengakuan Muliana Bayak ketika melihat paradoks pecalang ini:”… Pada suatu “upacara” pembukaan pameran seni rupa artist-artist dari Australia, yang diselenggarakan pada galeri milik seniman beken Bali di wilayah Denpasar, ketika memasuki pelataran parkir, saya sangat terkejut karena melihat palang perintang jalan bertuliskan “Hati-Hati! Ada Upacara Adat!!” lengkap dengan guardians sepasukan pecalang. Pada awalnya saya menjadi ragu, apakahundangan pameran seni rupa itu benar? Ataukah saya salah membaca tanggal yang tertera pada undangan? Ataukah hari ini Kajeng Kliwon yang bertepatan dengan penyelenggaraan suatu penyelenggaraan suatu upacara agama…”11
Paradoks budaya Bali dan identitas ke-Balian dipertanyakan dalam pernyatan karya Wayan Suja, Identitas Bali, 2002, 180X145, mixed media. Dalam visual karya, seorang lelaki Bali berkain dan berkaca mata hitam dengan tulisan “Bali Asli”, dengan latar belakang poleng (warna hitam putih) ditemani oleh seekor anjing yang menggantung tulisan “Bali Campuran”. Sebidang kanvas itu diberi judul besar “Dicari…Berindentitas Bali”. Pembongkaran identitas ke-Balian juga dinyatakan oleh Puja dalam Not Proud Being a Balinese, 2003, 150×150 cm, akrilik di atas kanvas. Gambar seorang lelaki (potret diri pelukis) digandengkan dengan tulisan putra daerah disebelahnya. Karya Suja dan Puja dalam pernyataannya seolah ingin mempertanyakan pengentalan identitas darah (soroh) yang sekarang makin marak di Bali. Ini ditunjukkan dengan banyaknya organisasi soroh yang lahir. Diantaranya sanak Pasek dan Maha Semaya Pande untuk mengambil contoh. Adakah ini sebuah kebingungan bagi orang Bali yang memakai senjata etnis atau garis darah di Bali untuk menghadapi kehidupan ini? Ini ditengah paradoks bagaimana manusia Bali hidup ditengah dunia yang katanya modern, pop dengan berbagai gaya hidup konsumerisme, free sex, drugs, dugem dan anti kemapanan.
Dalam fenomena kebudayaan yang akrab bagi Bali di desa-desa adalahBazaar, penggalian dana. Seakan merayakan gaya hidup mewah, konsumtif dan foya-foya. Ironisnya adalah dana dari foya-foya, mabuk-mabukan bahkan mengarah ke kekerasan ini untuk membangun pura atau persiapan melaspas atau ngusaba desa (upacara persembahyangan tempat suci, tempat tinggal, mengupacarai desa) misalnya. Sama seperti tajen yang berjudi untuk membangun pura. Pernyataan kritik fenomena kebudayaan kontemporer Bali ini dinyatakan pada karya Dodit, Kupon Penggalian Dana, 3 panel vertikal, 80×160 cm, mixed media, 2002. Karya ini menyindir kupon bazaar yang akrab kita lihat berserakan jika disebuah Banjar (tempat komunitas adat di Bali) yang dihias, penduduk dan pengunjungnya memenuhi jalan, ada plang Hati-Hati! Ada Upacara Agama (apakah bazaar, acara hura-hura, mabok-mabokan ini acara agama?) atau pecalang yang berjaga dengan tegak.
Lain lagi dengan karya Mulyana Bayak dalam The God Mustn’t Be Crazy Anymore, instalasi dinding, 2003. Tiga plangkiran (tempat menghaturkan sesajen di kamar-kamar bagi orang Hindu Bali) yang dicat dengan warna kuning, biru dan orange dan diisi botol coca-cola, bir , sprite. Dalam ritual Hindu Bali sangat sering kita lihat botol coca-cola dan sejenisnya dimanfaatkan untuk tempat tabuh (brem dan arak untuk upacara ritual di Bali) atau untuk tempat tirta (air suci). Atau sudah mulai masuknya simbol-simbol modern, ikon pop dalam ritual di Bali.
Gejala fasisme di Bali –dengan sweeping dan razia pada penduduk pendatang– menjadi pernyataan karya-karya dari Rocky Christian Olii. Just Shoot Me!, 2003, kaos sablon. Yang menarik dari karya Rocky adalah karya ini yang melekat pada dirinya. Sebuah kaos akan dipakainya dengan gambar depan sasaran target dan bertuliskan “Shoot Me”, (Tembak, Tuduh Aku), dibelakangnya bertuliskan Outsiders (orang luar). Karya ini seolah pernyataan bahwa sebagai orang luar (pendatang) saat ini di Bali hanya menjadi sasaran amukan orang Bali—lewat razia, pendataan penduduk kerena bingung terjadi bom. Memang dalam pameran kali ini hanya Rocky yang orang luar Bali. Ada juga karya Puja lewat Awas Illegal, 2003, 60X80, akrilik on canvas yang menyatakan bagaimana kartu pendatang saat ini sangat berharga di Bali. Lewat www.kippem.com, yang ditulis dibawah karya menunjukkan bagaimana Kartu Identitas Penduduk Pendatang Musiman ini sangat meneror dengan arogansi pecalang yang datang dini hari untuk melakukan razia penduduk.
BEBERAPA KRITIK
Keberanian kritik terhadap kebudayaan Bali oleh TAXU adalah sebuah modal untuk melakukan pembongkaran ulang pemikiran budaya Bali, tapi satu hal dalam paradoks tradisi dan modern –lebih lanjut kontemprer dan postmodern– adalah bagaimana representasi dan persepsi tentang ketradisian yang berjarak dari realitasnya kini yang dipahami oleh masyarakat Bali dan Indonesia12 . Di sinilah rangkaian studi post-kolonial tentang persepsi dan representasi Timur oleh Barat menjadi acuan kritiknya. Ketradisian Bali –dengan simbol, mitos, dan kebudayaan yang dikritik TAXU–jangan-jangan diciptakan oleh Barat (arus utama peradaban kebudayaan) yang sama sekali jauh dari realitas Timur (Bali/Indonesia). Studi-studi tentang kebudayaan di Bali yang dilakukan sarjana Barat awalnya terkesan eksotis, pulau sorga, damai layaknya pamflet promosi pulau kunjuangan wisata. Orientalisme –begitu Edward Said menyebut telah terjadi hegemoni dan imperialisme bahkan membunuh realitas timur karena strukturnya meniadakan kemungkinan dunia timur merepresentasikan dirinya13 .
Lalu apa perspsi kita tentang (kebudayaan) tradisi yang sering menuai kritik? Dalam bingkai seni rupa, adalah sebuah ruang dalam pertarungan perbedaan persepsi, kerangka acuan, kepercayaan estetis dan sudah barang tentu bebas dengan ekspresi dan pemikirannya masing-masing. Selanjutnya apakah kita perlu menyarikan dan mencari benang merah kritik kebudayan Bali dalam sebuah nilai baru tentang kebudayaan Bali? Pertama, sudah barang tentu ada yang ingin untuk membuat sebuah “kebenaran” tentang kebudayaan Bali dan mendefinisikan serta menguraikannya secara baku dan mapan. Kini kelompok pertama ini tentunya terwakili dan terinspirasi dengan keagungan dan romantisasi jayanya tradisi. Persepsi mereka tentang kebudayaan Bali tidak sesuai dengan realitas dan kembali berpikir untuk mengulang tradisi dalam waktu yang modern (masa kini). Sejujurnya, peta pemikiran seperti inilah yang kini mendominasi masyarakat Bali: imajinasi keagungan dan kejayaan tradisi masa lampau (bukankah bentukan?)
Bayangan akan tradisi –yang masih kuat di desa-desa di Bali, lukisan gaya tradisi Kamasan, Ubud, Batuan dan lain sebagainya– masih saja kuat, meskipun sudah bergeser menjadi produksi akibat arus utama pasar dan pariwisata. Tapi peta pemikiran modernpun –dalam seni rupa– kini telah menuai kritik. Seni lukis Bali yang masih mengangkat ikon tradisi kini latah dianggap menjadi seni rupa modern Bali, berdasarkan kategori melewati generasi Pita Maha, Ubud, Kamasan. Tapi apakah memang modern?
Kritikus seni rupa berpengaruh Clement Greenberg menyatakan dalam seni rupa, esensi modernisme terletak pada penjelajahan(berdasarkan kritik diri) idiom seni patung, arsitektur, seni lukis. Pencarian (dan penemuannya) sangat tergantung pada kemampuan menjaga kemurnian idiom-idiom itu.14 Lalu dimana letak karya Klinik Seni TAXU ini?
Jika dalam banyak karya pelukis Bali terdahulu –Erawan, Gunarsa, Sika, dan Sanggar Dewata Idonesia pada umumnya– persepsi dan representasi tradisi memang dipertanyakan lewat karyayang memakai kekuatan ikon tradisi sebagai jualannya. Bagaimana juga kesakralan dan kemurnian idiom-idiom poleng (hitam-putih) dipakai sebagai kekuatan dan mempromosikan religiusitas dan taksu Bali (yang entah seperti apa bentuknya?). Lihat misalnya karya-karya Erawan yang masih akrab menggunakan poleng, Gunarsa yang mendistorsi legong atau Sika yang mengumbar karya-karya abstrak dengan kekuatan magis dan mistisnya Bali.
Kedua, adalah pemikiran untuk perubahan-perubahan radikal untuk kebudayaan dan terus menrus mencari bingkai baru. Kelompok kedua ini biasanya yang terus melakukan kritik dan pembaharuan dalam kebudayaan. Yang berada dalam kelompok oposisi, kelompok minoritas yang terpinggirkan karena kelompok arus utama (dominan) dalam perkembangan peradaban, kesenian dan kebudayaan Indonesia (bali). Perubahan radikal yang terus menerus dan mencari format serta bingkai tanpa henti. Jika melihat statement karya dalam pameran ini, sudah barang tentu Klinik TAXU memilih jalan kedua, yang ingin perubahan radikal dan mencari peta-peta pemikiran baru tentang kesenian dan kebudayaan Bali.
I Ngurah Suryawan, Kritikus Seni Rupa, tinggal di Denpasar
1.Pleidoi Bagi Kegagalan Lahirnya Maestro Perupa adalah judul artikel yang dimuat di Harian Nusa, Minggu 25 Februari 2001. Sedangkan kalimat lanjutannya adalah alenia pembuka dari artikel tersebut. Tulisan ini masih dalam rangka perdebatan pameran seni rupa Mendobrak Hegemoni, Kamasra STSI Denpasar di Lapangan Puputan Badung 23-24 Febrtuari 2001.
2 Kutipan dialog antara Harry Potter dan Galfendorf dalam Harry Potter and The Chamber Of Secret. Cerita petualangan karya JK Rowlling yang difilmkan.
3 Dalam undangan dan pamfletnya–apakah komunitas ini selalu terkesan kontroversial –terdapat gambar Imam Samudra yang kepalanya diganti dengan kepala Simpanse. Juga tulisan baju yang dituliskan I Confess (Saya mengaku).
4 Lihat pamflet Isu paling Gress!!! yang sangat sederhana. Berisi pemaparan beberapa infrastruktur seni rupa dengan segala kritiknya. Diantaranya Media Massa: Kritikus seni cenderung sebagai agen promiso dan periklan, atau Seniman: seniman terikat kontrak dengan gallery yang akhirnya membelenggu kemerdekaan berkreasi. Lainnya ada pokok kritik untuk Gallery, Museum, Art Shop, kompetisi dan spekulan seni.
5 Karya yang paling mewakili semuanya tentunya adalah manifesto Kebudayaan yang berisi kecaman pada jurnalis, kritikus juga dosen-dosen malas di STSI Denpasar untuk berhenti. Dengan gaya kalimat plesetan dan bercanda. Yang lainnya diantaranya Potret Nyoman Erawan mirip Gorilla, Art Ne Pis (plesetan Art and Peace, proyek miliaran Made Wianta), Sangkar Dewata Indonesia (plesetan untuk Sanggar Dewata Indonesia) dll. Lebih lengkap lihat katalog Mendobrak Hegemoni, 2001.
6 Lebih lengkap mengenai rekaman dialog STSI-Himusba-SDI, Bali Post Maret 2001 memuat secara berseri isi dialog tersebut. Dialog ini tanpa mengundang Kamasra, tapi dihadiri oleh Senat Mahasiswa STSI Denpasar. Anehnya Kamasra sempat membuat dialog dengan mengundang semua yang merasa tersinggung dengan Mendobrak, tapi semua tidak ada yang datang. Iklan permintaan maaf STSI Denpasar juga dimuat di Bali Post Maret 2001.
7 Buletin Suaka misalnya terbit setelah katalog Mendobrak Hegemoni. Isinya tentang Pembelaan dari Kamasra dalam Buku Putih Kamasra-gate, Kritik STSI Denpasar. Lihat Buletin Suaka edisi Maret 2001.
8 Lihat pamflet Pesta Kapitalisme Bali, juga sub judul Pemerintah Kolonial Bali yang menyediakan dana kurang lebih 1 milyar rupiah untuk pesta yang membosankan dan layaknya seperti pasar malam ini. Selebaran ini juga tersebar saat berlangsungnya pembukaan PKB di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali 16 Juni 2001.
9 Lebih lengkap lihat terbitan Kronologis Pesta Kapitalisme Bali, Seputar Aksi Pameran Kontra PKB, Juni 2001.
10 Lihat terbitan perdana Buletin Seni Rupa KITSCH Agustus—September 2002
11 Lebih lengkap lihat tulisan Muliana Bayak dalam katalog ini, khususnya tentang konsaep karya Pecalang Uniform. Lihat artikel Paradoks Bali: Pecalang, Simbol Religius, Paradoks Sesaji dan Kritik Bali, Katalog TaXu, Hati-Hati! Ada Upacara TAXU, Januari 2003.
12 Lihat Artikel Jim Supangkat, Menyela Arus Utama, Kalam 1994.
13 Lihat Edward Said, Orientalism, 1978. Dalam Jim Supangkat, ibid
14 Lihat Jim Supangkat, Menyela Arus Utama , Jurnal Kebudayaan Kalam, 1994.

Bangkitkan Taksu Bali dan Lestarikan Budaya lewat Sanggar Seni Surya Chandra
18:10, Posted by simple, No Comment
Lantunan syair itu terdengar merdu mengawali peresmian sanggar multi-etnik lintas budaya Surya Chandra di Puri Gede Karangasem. Tampilan beragam seni dan budaya dari berbagai daerah oleh para seniman tersohor di Karangasem menambah acara yang berlangsung Kamis (17/7) malam lalu makin meriah.
Kegiatan yang dikemas secara apik tersebut melibatkan 200 seniman mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Suguhan tarian Surya Chandra ciptaan A.A. Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.M. membuat pengunjung yang datang makin terpukau.
Sanggar Surya Chandra menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang datang ke Bali, khususnya di Karangasem. Di tempat ini, semua orang dari berbagai suku, adat, budaya dan agama bisa belajar beragam kesenian Nusantara.
Tak mengherankan, tempat ini dilengkapi sarana-prasarana kesenian seperti tabuh dan gong yang didukung pembina dan pelatih yang berasal dari berbagai unsur. Uniknya, pengunjung bisa belajar tarian Surya Chandra di sini.
A.A. Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.M., pembina Sanggar Surya Chandra menuturkan, berdirinya sanggar multi-etnik ini sebagai cara mewujudkan misi dan visi Puri Gede Karangasem yakni sebagai pusat inspirasi seni, budaya dan spritual.
Sanggar Surya Chandra membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua lapisan masyarakat Karangasem, terutama pecinta seni, budaya dan spiritual baik anak-anak, remaja dan masyarakat umum untuk belajar menggali potensi seni dan budaya yang masih terpendam agar dapat dikembangkan sehingga terpelihara dengan baik.
Surya Chandra juga menjadi wadah kreativitas seni, vokal, tari, dan tabuh. "Untuk itu Puri Gede Karangasem bermaksud menampung semua seniman dalam satu wadah sanggar seni lintas budaya Surya Chandra," ujar wanita yang karib disapa Gung Tini ini.
Surya Chandra sekaligus bisa menjadi salah satu daya tarik pariwisata yang bisa menunjang kesejahteraan masyarakat Karangasem dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Menurut Gung Tini, tak hanya seniman yang bisa berkarya dalam seni dan budaya, seluruh lapisan masyarakat pun bisa belajar seni dan budaya guna mewarnai kesemarakan khasanah seni dan budaya. "Bukankah seni dan budaya mencerminkan tingginya martabat manusia," ucapnya.
Menurut Gung Tini sebagai Purwaning Hulu Jagat Bali, Karangasem harus mampu mempertahankan dan melestarikan budaya daerah. "Dengan hadirnya sanggar Surya Chandra, Puri Gede Karangsem akan memunculkan parbe taksu jagat Bali yang akan menjadi kekuatan spiritual dalam menjaga kelestarian dan keajekan Bali," katanya. Gung Tini menambahkan masyarakat tak perlu risau, belajar seni dan budaya di sanggar ini tak dikenakan biaya. —lik
Susunan Pengurus Sanggar Seni Surya Chandra Puri Gede Karangasem
Penasihat : A.A. Bagus Ngurah Agung, S.H., M.M.
Pembina : - Kadis Pendidikan Kabupaten Karangasem
- Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
- A.A. Ayu Sasih
- A.A. Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.M.
- A.A. Ngurah Darma Sanjaya, S.H.
- A.A. Raka Sidan
Ketua : Ida Ayu Ratih Ratna Dewi
Sekretaris : Ni Made Suradnyani
Bendahara : Mekele Kusumasari, A.A. Mas Sri Andari
Seksi Musik & Vokal : - I Gusti Bagus Bengkel
- I Kadek Budiarta
- I Komang Juniantara
- Ibu Yanik
Seksi Tabuh : I Ketut Nanda
Seksi Tari :- Dudek Suhardika
- Dewa Rupania
- Ni Made Suradnyani
Peelengkapan: I Komang Adi Swastika
Jumat, 30 Oktober 2009
Taksu dan Jengah untuk hidup

Taksu dan Jengah
Atha chet tvam imam dharmyam, samgramam na karishyasi
Tatah svadharmam kirtim cha, hitva papam avapsyasi (Bhg.II.33)
Artinya : Tetapi jika engkau tiada melakukan perang menegakkan kebenaran ini, meninggalkan kewajiban dan kehormatanmu maka dosa papalah bagimu.
MODERNISASI kehidupan manusia serta perubahan sosial yang berjalan cepat, membawa beraneka ragam kemajuan dan sekaligus berbagai masalah. Dampak negatif dari suatu proses perubahan itu seperti meningkatnya kemiskinan, krisis ekonomi, korupsi, perselingkuhan, pemutusan hubungan kerja, penyebaran AIDS/HIV dan penyakit masyarakat lainnya.
Dari segi agama dapat dijelaskan bahwa problematik kehidupan ini dapat terjadi karena manusia tidak siap menerima dan menghadapi kemajuan tersebut. Dalam dirinya tidak ada jiwa tenang, tidak ada keseimbangan antara kehidupan materiil dan kehidupan spiritual, ketidakseimbangan antara kehidupan berkebudayaan dan kehidupan beragama, maka munculah kehidupan dimana siapa yang kuat memakan yang lemah, yang bergelimangan harta menghamburkan uang tanpa arah, yang miskin terus merana terkapar di hamparan debu dan lumpur. Untuk bangkit dari keterpurukan itu, dapat kita menyimak kutipan kitab suci Bhagawadgita II.33 di atas. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan perkataan “perang” dan “ksatria” pada sloka tersebut adalah mengandung pengertian yang lebih mendalam dan bersifat spiritual. Perang menegakkan kebenaran disini dimaksudkan lebih dari membela tanah air, bangsa dan agama, yaitu pergulatan bhatin antara yang benar dan yang salah. Mereka yang menghindarinya karena perasaan lemah dan takut adalah berdosa. Demikian pula yang dimaksud dengan perkataan “ksatria” bukanlah asal kelahiran atau keturunan melainkan melainkan kondisi psikophisik seseorang yang memiliki sifat-sifat dan pengertian akan swadharma (menjalankan kewajiban sendiri).
Untuk bangkit dari keterpurukan itu, dapat kita menyimak kutipan kitab suci Bhagawadgita II.33 di atas. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan perkataan “perang” dan “ksatria” pada sloka tersebut adalah mengandung pengertian yang lebih mendalam dan bersifat spiritual. Perang menegakkan kebenaran disini dimaksudkan lebih dari membela tanah air, bangsa dan agama, yaitu pergulatan bhatin antara yang benar dan yang salah. Mereka yang menghindarinya karena perasaan lemah dan takut adalah berdosa. Demikian pula yang dimaksud dengan perkataan “ksatria” bukanlah asal kelahiran atau keturunan melainkan melainkan kondisi psikophisik seseorang yang memiliki sifat-sifat dan pengertian akan swadharma (menjalankan kewajiban sendiri).
Sejak dalam kandungan dan lahir sebagai manusia dewasa, manusia memiliki dua sumber kekuatan yang perlu dihayati dan dikembangkan. Dua sumber kekuatan yang dimaksud adalah “Taksu dan Jengah”. Taksu adalah kekuatan dalam yang memberi kecerdasan dan keindahan. Dalam kaitan dengan aktivitas budaya, taksu sebagai anugrah Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, penyerahan diri pada bidang tertentu secara murni dan disiplin. Taksu merupakan pangkal aktivitas dan landasan kemampuan dalam menghasilkan karya-karya monumental.
Konteks budaya, perkataan “jengah” memiliki konotasi sebagai semangat guna menumbuhkan inovasi untuk bangkit dari keterpurukan. Jengah merupakan dasar sifat-sifat dinamik yang menjadi pangkal segala perubahan dalam kehidupan masyarakat. Taksu dan jengah bagaikan sinar matahari dan sinar bulan purnama. Sinar matahari yang memancar di siang hari memberikan pencerahan dan penerangan seluruh mahluk agar memahami dan mengerti hidup. Sedangkan sinar bulan purnama di malam hari memberikan penerangan kepada semua mahluk bahwa hidup ini sesungguhnya sangat indah. Taksu dan jengah adalah dua kekuatan yang saling isi mengisi sehingga memungkinkan terjadinya transformasi budaya secara terus menerus melalui proses pemeliharaan, pelestarian, pembinaan dan pengembangan.
Dalam upaya menggali dan mengembangkan dua sumber kekuatan tersebut, sudah tentu tidak hanya berhenti pada tataran tradisionalis, melainkan mampu berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan zaman yaitu melalui penguasaan ilmu dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam aplikasinya dilandasi oleh nilai-nilai etika, moral dan agama, maka kita memiliki pegangan yang kuat dan kokoh dalam menghadapi berbagai perubahan, dan tantangan yang datang baik dari dalam diri manusia maupun dari luar diri manusia. Walaupun telah menguasai ilmu dan teknologi, namun belum melaksanakan nilai-nilai etika, moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari, maka selamanya mereka tidak bisa mencapai hidup spiritual, sebab ia tidak dikendalikan oleh jiwanya melainkan oleh egonya.**
Taksu-Memasak dan Sejarah

Klinik Seni Taksu - Memasak dan Sejarah
Pameran ini berangkat dari sebuah perdebatan panjang tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Bali sepanjang perjalanan sejarah ini (1965). Sejarah peradaban manusia adalah sejarah penaklukan, sejarah penindasan, dan penghilangan antara sesamanya. Salah satunya pembantaian besar-besaran terhadap orang yang dituduh anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Tema pameran mencoba mencari kaitan antara memasak dan sejarah. Memasak sebagai aktivitas mengolah sesuatu (bahan makanan dan bumbu) sedangkan sejarah sebagai hasil racikan gurih penuh bumbu mitos atau heroisme oleh pihak penguasa, yang terkadang terlewat gurih sehingga menyerupai babad dan mitologi. Hubungan yang terlihat adalah seputar “kegiatan meracik dan hasilnya”, apabila dilebarkan mungkin persilangan dua tema tersebut kelak dapat menghasilkan panduan-panduan seperti “Sejarah Memasak”, “Memasak dan Sejarah”, atau mungkin “Memasak Sejarah”.Yang terakhir itu bisa berkonotasi "memasak sejarah hingga matang untuk disajikan di atas meja makan" (lihat: katalog pameran "Memasak dan Sejarah"). Visualisasi di ruangan pameran "Memasak dan Sejarah" menampilkan keberagaman medium, mulai dari lukisan, woodcut, fotokopi, instalasi, performance art dan video. Performance yang hadir dalam pameran tersebut, sebagai pembuka peresmian pameran "Memasak dan Sejarah" berupa demo memasak dalam ruang pameran dengan bahan dasar umbi ketela pohon yang langsung dibawa dari Bali. Keberagaman medium ini tergabung menjadi satu dalam sebuah karya kolektif. (Sumber: http://gudeg.net/news/2004/06/2464/Pameran-Memasak-dan-Sejarah-Berangkat-dari-Perdebatan-Tragedi-Kemanusiaan.html). Ada juga Artist Talk, Pemutaran film "Bali tahun 30an" dan "Mass Grave", disusul diskusi bersama Dr. Budiawan sebagai narasumber. Pameran ini dikerjakan oleh komunitas Klinik Seni Taxu, Bali.
Taksu Bali dalam Membangun Hidup

Membangun Hidup ''Mataksu''
Adanya Pelinggih Kamulan Taksu di setiap Merajan sebagai Batara Hyang Guru bagi keluarga Hindu di Bali sesungguhnya mengandung nilai-nilai yang universal. Mataksu artinya dapat melihat sesuatu aspek kehidupan dengan pandangan yang multidimensi. Sesuatu itu tidak dipandang dari sudut pandang mata duniawi semata. Seseorang akan dapat hidup mataksu apa bila memiliki struktur diri yang ideal.
============================================================
Struktur diri yang ideal di mana Atman sebagai unsur tersuci dalam diri dapat memancarkan kesucian melalui kesadaran budhi tembus pada kecerdasan pikiran dan kesempurnaan indria. Struktur diri yang ideal itu harus dibangun sejak manusia diletakkan dalam rahim ibu. Spirit dan Catur Sanak dianggap sebagai sumber taksu. Karena spirit Catur Sanak itu adalah dari Atman.
Tanpa ada Atman bersemayam dalam diri seorang ibu tentunya Catur Sanak tersebut tidak bisa berfungsi apa-apa. Ia hanyalah fisik belaka yang dibangun dari lima zat alam yang disebut Panca Maha Bhuta. Yang distanakan di Pelinggih Kamulan adalah aspek spiritnya sebagai pancaran dari Atman. Sedangkan Atman dalam Upanisad tidak lain dari Brahman.
Kamulan Taksu itu disebut sebagai Bhatara Hyang Guru. Dari dua pelinggih itulah mulai dibangun hidup mataksu, artinya hidup dengan pandangan luas yang multi dimensi. Dengan adanya Pelinggih Kamulan sebagai Pelinggih Sang Hyang Atma ini berarti Atman sebagai guru seperti dinyatakan dalam Vana Parwa.
Pelinggih Kamulan adalah stana Sang Hyang Atma sebagaimana dinyatakan dalam Lontar Usana Dewa dan Lontar Gong Wesi. Kedudukan Kamulan sebagai stana Sang Hyang Atma adalah simbol sakral untuk memotivasi umat Hindu agar secara terus-menerus mengembangkan pendidikan kerohanian dalam keluarga. Pendidikan kerohanian itu untuk mengutamakan eksistensi kesucian Atman dalam diri umat.
Atman yang tiada lain adalah Brahman tentunya selalu memancarkan kesucian. Tetapi pancaran kesucian Atman itu sering ditutupi oleh avidia atau kegelapan budhi, manah dan indria bagaikan awan gelap menutup sinar matahari yang selalu memancar. Karena itu budhi, manah dan indria harus disucikan dengan ilmu pengetahuan suci. Karena itu dalam Manawa Dharmasastra V.109 dinyatakan bahwa ''vidya tapobhyam bhutatma suddhyati''.
Artinya Atman disucikan dengan ilmu pengetahuan suci dan tapa brata. Ini berarti agar manusia selalu berguru untuk mendapatkan tuntutan Atman maka senantiasalah dalam keluarga Hindu itu mengembangkan hidup berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengendalian diri dengan tapa brata. Dengan demikian hidupu akan mataksu. Taksu akan hilang kalau hidup ini tidak mengikuti tuntunan ilmu pengetahuan suci. Resi Bisma kehilangan taksu saat tinggal di Astina. Karena setiap hari disuguhi makanan hasil kejahatan dan dimasak oleh orang-orang jahat. Saat itu Duryudana sebagai Raja Astina.
Makanan yang didapat dengan cara melanggar dharma saja kesucian Atman tidak memancarkan dalam diri sehingga taksu menjadi hilang. Tujuan Tapa Brata dan Vidya itu untuk mendidik, melatih dan membina indria, manah dan budhi menjadi media untuk memancarkan kesucian Atman. Dari pancaran kesucian Atman itulah akan didapatkan taksu. Palinggih Taksu di Merajan Kamulan itu sebagai pemujaan spek spirit dari Catur Sanak. Secara langsung unsur-unsur Catur Sanak itulah yang membentuk janin menjadi jabang bayi.
Di dalam ilmu pendidikan dikenal adanya pendidikan prenatal artinya pendidikan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Dari anak dalam kandungan itulah sudah ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang utuh, baik dalam fisik maupun mental spiritual. Setelah ia lahir sudah membawa bibit-bibit unggul untuk diberikan pendidikan agar kelak menjadi suputra yang mataksu.
Dengan demikian sudah sangat tepatlah leluhur umat Hindu di Bali menyebutnya Merajan Kamulan itu sebagai tempat memuja Batara Hyang Guru. Di Merajan Kamulan itulah sudah ditanamkan nilai-nilai pendidikan yang seimbang antara pendidikan untuk membangun jiwa dan raga yang seimbang.
Dalam Nitisastra VIII.3 ada dinyatakan suatu kewajiban orangtua untuk melahirkan putra atau disebut Sang Ametwaken. Hal ini mengandung maksud agar seorang ayah dan ibu dalam menyiapkan kelahiran putranya benar-benar melalui persiapan yang matang, baik fisik maupun mental spiritual. Apalagi sudah terbentuknya janin dalam kandungan ibu.
Keadaan Sang Catur Sanak seperti ari-arinya, darah, yeh nyom dan lamas-nya terpelihara dengan perawatan yang telaten. Menjaga kesehatan ibu yang mengandung secara prima itulah awal pendidikan anak manusia agar kelak ia menjadi putra yang mataksu.
Adanya Pemujaan Batara Hyang Guru di Kamulan Taksu itu tidaklah semata-mata hanya sebagai media melakukan ritual keagamaan Hindu yang bersifat formal belaka. Di balik itu ada pesan-pesan pendidikan yang amat mendasar sehingga tempat pemujaan itu disebut sebagai palinggih Batara Hyang Guru. Apalagi di dalam ajaran Hindu dikenal adanya pendidikan seumur hidup lewat ajaran Catur Asrama.
Saat masih dalam Brahmacari Asrama belajar dharma untuk mendapatkan Guna Vidya atau ilmu tentang keterampilan untuk mencari nafkah agar dapat melangsungkan kehidupan ini. Grshastha Asrama pendidikan untuk dapat hidup mandiri. Kemandirian itulah ciri seorang Grhastha.
Selanjutnya saat menjalankan Wanaprastha Asrama menjadi penasihat atau sawacana gegonta yang wajib dipelajari terus. Saat menginjak Sanyasa Asrama harus berguru untuk melepaskan Atman dengan sebaik-baiknya kembali ke alam niskala. Inilah konsep belajar seumur hidup menurut ajaran Hindu. Proses belajar yang terus-menerus itu dilakukan dengan benar dan tepat.
Proses belajar yang benar dan tepat itu sesuai dengan tahapan Catur Asrama. Setiap Asrama yakinlah ada yang muncul lebih sukses dari yang lainnya. Dengan demikian setiap Asrama akan memiliki tokoh-tokoh mataksu. Proses pendidikan informasi dalam keluarga ini harus terus digerakkan melalui pemujaan Batara Hyang Guru di Kamulan Taksu.
Dari Kamulan Taksu inilah hendaknya digagas terus pendidikan untuk membangun keseimbangan kualitas hidup fisik material dan mental spiritual dengan belajar terus-menerus. Apalagi dalam Pustaka Wrehaspati Tattwa 33 ada dinyatakan bahwa salah satu ciri hidup sukses adalah Adhyayana. Artinya belajar terus-menerus, tidak pernah merasa tamat belajar. Selanjutnya Tarka Jnyana artinya terus-menerus berusaha untuk mempraktikkan ilmu yang didapatkan. * wiana
Taksu Bali

Taksu Bali
Taksu di Bali sangata erat dengan kebudayaan Bali, untuk lebih memahaminya silahkan baca artikel berikut
Kegiatan seni bagi masyarakat Hindu Bali merupakan suatu refleksi kehidupan dalam upaya mengungkapkan esensi suatu karya yang mengandung kualitas keindahan, rasa bhakti yang berpedoman kepada nilai-nilai budaya tradisi. Kegiatan seni terwujud dalam bentuk tarian, arsitektur tradisional, patung atau artifak, sastra, lukisan, dan sebagainya. Sedangkan makna dari kegiatan seni adalah sebagai wujud persembahan (Yadnya) kepada Sang Hyang Widhi Wasa dalam wujud karya seni.
Masyarakat Bali (Hindu) mengenal adanya suatu pedoman mengenai pencapaian kualitas untuk menghasilkan suatu karya bermutu, disebut taksu. Taksu sebagai landasan pencapaian kualitas seni lebih mudah dilihat, dirasakan dan dijelaskan melalui bentuk tarian, karena perwujudannya tampak secara visual. Berdasarkan hasil survey, taksu ternyata ada pada setiap bidang kegiatan.
Berdasarkan keterangan diatas, maka fokus penelitian ini untuk mengungkapkan pencapaian kualitas taksu pada bidang arsitektur rumah tradisional Bali, yaitu griya sebagai studi kasus. Penelitian tesis ini mempergunakan metoda penelitian kualitatif, tujuannya untuk memperoleh pandangan secara holistik dari mereka yang diteliti. Penelitian meliputi komposisi rumpun bangunan, pekarangan, natah (halaman), dan karakteristik penghuni.
Temuan-temuan yang diperoleh, taksu pada dasarnya merupakan landasan berpikir dalam upaya mengungkapkan nilai-nilai dan makna keindahan yang tertinggi. Berdasarkan keterangan di atas ditemukan tiga unsur penting yang saling mempengaruhi untuk tercapainya pemahaman nilai-nilai taksu, yaitu : undagi (arsitek), griya (karya), dan masyarakat umum (penghuni griya). Undagi dengan karyanya bila mendapatkan suatu pengakuan, penghargaan dari masyarakat dikatakan sebagai undagi metaksu dan griya metaksu. Metaksu adalah hasil apresiasi masyarakat sebagai penikmat karya, karena secara kreatif seniman tersebut telah mampu menghasilkan dan menyampaikan suatu karya yang memenuhi nilai-nilai yang hendak dikomunikasikan, berupa pesan-pesan estetik.
Inti dari pencapaian taksu menjadi metaksu, adalah didalam suatu karya tersembunyi subjektivitas undagi, dan masyarakat melihat sebagai suatu karya yang utuh (manunggal). Maka taksu dapat dikatakan semacam “ideologi” bagi masyarakat Hindu Bali; dalam pengertian sebagai suatu kumpulan nilai-nilai budaya asli daerah yang dijadikan landasan pemikiran, pendapat yang memberikan arah tujuan untuk mencapai kualitas dalam kehidupan.
Pencapaian pemahaman nilai-nilai taksu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi undagi karena akan berdampak dalam upaya menjaga kualitas keharmonisan dan keserasian antara bhuwana alit dan bhuwana agung, sesuai tujuan akhir hidup orang Bali, yaitu : mencapai kesejahteraan jagad dan mencapai moksa (keabadian akhirat).
Translate:
Artistic performance is a life reflection to the Balinese in their effort to reveal essence of product that contains attractiveness and devotion to traditional life, such as dancing, painting, sculpture or artifact, literature, traditional architecture, ect. While the artistic activity function in considered as the artist realization in offering (Yadnya) to their God, Sang Hyang Widhi Wasa in the artistic product format.
The Balinese Hindu society recognizes the existence of a process that they use as a guidance to achieve a quality artistic product, which is known as taksu. Taksu as a base to achieve high quality product, easily can be seen, felt, and explained in the forms of dancing since it has a visual form.
Survey indicates that taksu has exists on all forms of activities. Based on the above, this research has focused on taksu quality achievement in the field of traditional Balinese architecture, griya as a case study. A qualitative methodology is employed on this research in order to get a holistic view. The research consists of building structural composition, yards, and the occupant characteristics.
The finding : taksu in general is the basis of thought in an effort to reveal the highest quality value. There are three important factors interrelated to achieve understanding on taksu, namely : the undagi ( the traditional architecture), griya (product), and the general public (the griya occupant). If an undagi with his masterpiece, griya gets appreciation form the society, it is called that the undagi and the griya are metaksu. Metaksu is the general society appreciation as devotee, since the artist creativity has able to communicate values in the form of aesthetical messages.
The point of taksu to become metaksu in an undagi achievement is the undagi hidden subjectivity; the society sees it as a united product. Taksu for the Balinese Hindu could be said as their ‘ideology’, as a group of region original cultural values which is used as a base of their thought, opinion that give them guidance in achieving better quality in life. Achievement of taksu understanding is a very important matter to an undagi, as it has an effect in maintaining harmony between the micro and macro cosmos, in accordance to the ultimate Balinese goal in life; to accomplish universe prosperity and to achieve moksa (redemption/ eternity).